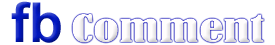JUDUL : HYPERMARKET, RAKSASA BARU DUNIA RITEL
----------------------------------------------------------------------------------
By : Bang Udin
Malam menunjukkan pukul 23.00 WIB ketika Cecep Harianja tak kunjung bisa memejamkan matanya. Sudah satu jam lebih ia merenungi nasib toko kecilnya di dekat perempatan Lebak Bulus yang kian hari semakin sepi. Sejak kehadiran Carrefour di kawasan itu, praktis omset tokonya yang menjual produk kebutuhan sehari-hari merosot tajam. Bila dulu bisa meraih omset Rp 500 ribu sehari, belakangan tinggal Rp 150 ribu saja. Bahkan kalau tengah sepi, omsetnya tak sampai Rp 100 ribu.
Kegelisahan Cecep hanyalah ekses kecil — bahkan sangat kecil — dari gelombang ekspansi besar-besaran hypermarket saat ini. Dalam 2-3 tahun terakhir, gairah bisnis hypermarket memang benar-benar tak terbendung. Format ritel ini mengeliat begitu pesat. Tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya (Jabotabek), bersamaan dengan itu juga merambah ke Bandung, Surabaya, Medan, Denpasar, dan seterusnya.
Awal 1990-an orang masih melihat Makro sebagai hypermarket yang eksklusif dari Belanda — terutama karena ada sistem keanggotaan untuk bisa belanja di sana — diikuti kehadiran Continent dan Carrefour secara hampir bersamaan tahun 1998, yang kemudian keduanya merger menjadi Carrefour. Sekarang, terlihat pemandangan baru: begitu banyak hypermarket bermunculan. Selain Carrefour dan Makro yang terus membiakkan diri (memiliki 15 gerai), kini ada Giant, Hypermart, Alfa, dan The Club Store. Hypermarket Giant yang dimiliki Grup Hero dan Dairy Farm sebut saja, hanya dalam waktu dua tahun (mulai beroperasi 2 Agustus 2002) sudah memiliki 10 gerai. Kini gerai Giant tersebar di Serpong, Bekasi, Cileduk, Cimanggis, Bandung, Surabaya dan juga Jakarta (Plaza Semanggi).
Agresivitas dan sambutan pasar yang cukup bagus pada Giant tampaknya menjadi pelipur lara tersendiri buat manajemen Hero, karena berarti mengeliminasi pesimisme gara-gara Supermarket Hero di berbagai tempat cenderung stagnan atau bahkan makin menurun. “Manajemen Hero kelihatannya sangat happy dengan kinerja Giant,” ujar seorang petinggi di asosiasi ritel yang tak bersedia disebut namanya.
Tidak hanya Giant, raksasa hypermarket asal Prancis, Carrefour, seharusnya lebih happy pula. Pasalnya, di antara para pemain hypermarket lain, Carrefourlah yang sekarang mendominasi, baik dari segi jumlah gerai maupun omset bulanan. Meski belum ada data riset yang menunjukkan dominasinya, dipastikan Carrefour adalah pemimpin pasar hypermarket saat ini. Jumlah 15 gerai yang dimilikinya sekarang, kemungkinan akan terus bertambah. Seperti saat ini Carrefour tengah menyiapkan pembukaan gerai baru yang cukup besar di Yogyakarta, tepatnya di Plaza Ambarukmo yang dikembangkan keluarga Kesultanan Yogyakarta, serta pembukaan di Blue Oasis City, Bekasi.
Grup Alfa tak mau ketinggalan. Alfa memiliki 25 gerai yang diposisikan sebagai gudang rabat. Gerai Alfa memang tak sebesar Carrefour atau Giant, tapi jauh lebih besar dari kelas supermarket. “Gudang rabat Alfa lebih tepat disebut sebagai compact hypermarket,” ujar Yongky Surya Susilo, Direktur AC Nielsen dalam sebuah seminar beberapa waktu lalu. Hypermarket ala Alfa ini juga sudah ada di luar Jabotabek, termasuk di Jember, Malang, Surabaya, Yogya, Cirebon, Bandung, Denpasar dan Makassar.
Grup Lippo juga termasuk salah satu pemain baru yang kini amat serius mengembangkan hypermarket melalui anak usahanya, PT Matahari Putra Prima (MPM). Dinamai Hypermart, pada tahun pertama, Grup Lippo langsung membuka empat gerai sekaligus: di Serpong, Solo, Tangerang dan Karawaci. Bahkan, kabarnya jumlah gerai masih akan terus bertambah, yakni dari reposisi gerai Matahari yang kinerjanya dianggap kurang bagus.
Danny Kojongian, Direktur MPM, menjelaskan, tahun 2005 pihaknya akan membuka 10 gerai baru Hypermart. Kota yang diincar antara lain Jabotabek, Medan, Makassar dan Manado. Untuk itu telah disiapkan anggaran Rp 400 miliar. Hingga tahun 2010, MPM menargetkan telah punya 50 gerai Hypermart, dan mulai 2007 diharapkan Hypermart mampu menyumbang 80% pendapatan MPM. Adapun MPM sendiri tahun 2004 diperkirakan memiliki omset total Rp 5,5 triliun.
Jadi, tidak bisa dipungkiri, hypermarket kini menjadi primadona baru pebisnis ritel. Dalam situasi persaingan yang sangat ketat ini, para pemain yang ada terus saja menambah jumlah gerainya. Manajemen Giant, misalnya, tahun 2005 menargetkan membuka 8 gerai baru. Sementara Makro siap menambah tiga gerai baru. “Tiga tahun ke depan kami menargetkan menambah 15 gerai baru,” kata Simon Collins, Presdir PT Makro Indonesia.
Selain pemain-pemain yang sudah beroperasi, kini terdengar santer sejumlah hypermarket asing juga siap masuk. Antara lain raksasa hypermarket asal Inggris, Tesco dan juga Bigzy.
Antusiasme dan agresivitas para pemain hypermarket tentu didorong oleh potensi pasar di Indonesia yang memang amat besar. Dengan jumlah penduduk sebesar 220 juta dan kenyataan pasar tradisional yang masih dominan (73%), menunjukkan bahwa peluang ritel modern terbuka lebar, termasuk buat hypermarket tentunya.
Belum lagi melihat kenyataan perputaran uang di bisnis ritel yang memang luar biasa besar. Tahun 2004, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menghitung, market size pasar ritel senilai Rp 330 triliun, meningkat dari tahun 2003 (Rp 300 triliun). Biro riset AC Nielsen juga menunjukkan, tren belanja di ritel modern memang semakin meningkat. Nilai penjualan tiap tahun meningkat hingga tiga kali lipat. Jika tahun 2002 cuma 12% konsumen yang belanja di gerai ritel modern, tahun 2003 meningkat menjadi 38%.
Data Aprindo tersebut paralel dengan hasil temuan AC Nielsen. Lebih lanjut Farquar Sterling, Direktur Pengelola AC Nielsen Asia Tenggara, menjelaskan pertumbuhan ritel hypermarket paling tinggi dibanding jenis ritel lain di Indonesia, mencapai 15%. Angka ini sama dengan pertumbuhan minimarket. Sementara supermarket adalah ritel modern yang pertumbuhannya paling kecil, hanya 7%. Yang paling menderita pasar tradisional, karena justru turun 8,1%. Jadi, secara tak langsung bisa dikatakan hypermarket telah menggerogoti potensi yang seharusnya dimakan supermarket dan pasar tradisional (wet market).
Sterling yang pernah menjabat Direktur Pengelola AC Nielsen Indonesia itu juga menjelaskan, kenaikan hypermarket khususnya karena didukung pertumbuhan konsumen urban berpendapatan Rp 1,25-1,8 juta. “Tahun 2004 persentase kelompok ini mencapai 27%. Konsumen kelas ini jumlahnya mencapai 22 juta orang,” ujar Sterling pada presentasi bertajuk Consumer Spending Power, Oktober 2004.
Data meningkatnya peran ritel modern khususnya hypermarket, juga ditunjukkan Handaka Santoso, Ketua Umum Aprindo yang juga Dirut PT Panen Lestari (Sogo). Saat ini pangsa pasar yang dikuasai ritel modern di Indonesia senilai Rp 35 triliun. “Ini hanya untuk total omset ritel modern dari para peritel yang menjadi anggota Aprindo,” Handaka menegaskan. Yang jelas dari tahun ke tahun kontribusi atau peran hypermarket memang makin besar. “Saat ini pangsa pasar hypermarket dari seluruh ritel modern sekitar 20%-25%,” tambah Handaka.
Sebenarnya bila ingin gampang melihat bagaimana pengaruh hypermarket terhadap bisnis ritel dan juga perilaku konsumsi bisa dilihat dari keberadaan Carrefour sendiri. Masih menurut AC Nielsen, Carrefour kini sudah menjadi peritel pemberi kontribusi terbesar pada penjualan produk-produk konsumsi yang tergolong fast moving consumer good (FMCG). Artinya, Carrefour juga mengalahkan jaringan ritel Grup Salim (Superindo dan Indomaret), padahal jumlah ritel minimarket Grup Salim mencapai ribuan gerai, serta dikenal punya kedekatan dengan sumber pasokan (Indomarco dan Grup Indofood). Dengan demikian, Carrefour sudah membuktikan kehebatannya sebagai representasi dari gelombang besar kehadiran hypermarket.
Pengamat ritel Syamsul Munir melihat, hypermarket berkembang pesat di Indonesia karena mampu menawarkan harga paling rendah, produk selalu fresh (perputarannya cepat), area belanja luas dan jumlah produknya lengkap. “Pendeknya mereka bisa mewujudkan konsep sell everything,” katanya. Menurut Syamsul, hypermarket disambut bagus di Indonesia sebab formatnya cocok dengan karakter konsumen di Indonesia yang menjadikan belanja sebagai bagian dari rekreasi. “Ingat, sebagian besar konsumen di Indonesia merupakan weekly buyer,” tutur Syamsul.
Sementara itu, praktisi distribusi Djoko Tata Ibrahim mengamati pesatnya perkembangan hypermarket disebabkan tuntutan zaman. Masyarakatnya semakin maju, sistem ekonomi makin terbuka, dan pendapatan masyarakat meningkat. “Konsumen butuh kenikmatan untuk memilih,” Djoko yang juga Presdir PT Intermas Tata Trading menjelaskan. Malahan Djoko mengamati sebenarnya perkembangan hypermarket di Indonesia terbilang terlambat 20 tahun. Di negara maju itu merupakan fenomena lama. Tentu hal ini tak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang baru sekarang siap untuk pengembangan hypermarket.
Perkembangan hypermarket sebenarnya juga seiring maraknya segmentasi pasar. Kini, hampir semua produk di-leverage ke dalam banyak segmen. Contohnya produk sampo, sekarang ada sampo bayi, remaja dan dewasa. Belum lagi berdasarkan fungsinya, ada yang menonjolkan kandungan vitamin, antiketombe, penghitam, hingga ke produk vitalitas. Hampir semua produk mengalami segmentasi. Otomatis hal itu butuh pola merchandising yang baik dan tertata.
“Pasar tradisional tak menampung aspirasi ini sebab lokasinya terbatas. Hypermarket paling cocok,” lanjut Djoko. Dari sini bisa dimengerti kalau sebagian besar hypermarket di Indonesia laris manis diserbu pembeli. Djoko benar, apalagi kenyataannya di Indonesia hypermarket bisa berdiri di tengah kota sehingga memudahkan jarak berbelanja. Meski sebenarnya hal ini merugikan pedagang kecil sekelas papa-mama shop. Ini dimungkinkan terjadi di Indonesia sebab belum ada ketentuan yang mengatur. “Negeri ini soft country. Indonesia yang sebesar ini belum punya UU ritel,” ujar Syamsul.
Sudah pasti, sukses penetrasi hypermarket keseluruhan telah menempatkan jenis ritel ini sebagai mesin uang dahsyat yang baru. Omset penjualan yang mereka raih cukup mencengangkan. Tak terlalu sulit menghitung omset mereka, terutama dengan melihat dari jumlah transaksinya. Seorang mantan eksekutif hypermarket menjelaskan, di gerai sebesar Carrefour, Giant atau Hypermart, tiap hari paling tidak terjadi 2.500-3.000 transaksi.
Bila dirata-rata nilai per transaksi Rp 300 ribu (dengan perkiraan harga-harga barang kebutuhan saat ini), penjualan per hari Rp 750-900 juta. Malahan bukan rumor lagi bahwa beberapa gerai Carrefour bisa meraih omset Rp 1 miliar per hari. “Pada masa peak season memang bisa mencapai Rp 1 miliar per outlet,” ujar Handaka yang juga praktisi ritel itu menghitung. Yang dimaksud peak season antara lain saat weekend dan hari-hari besar. Dari sini bisa dihitung berapa omset tahunan Carrefour yang punya 15 gerai itu.
Umumnya, masing-masing hypermarket memang punya gerai andalan yang omsetnya paling besar. Carrefour sebut saja, mesin uangnya yang paling besar berproduksi adalah gerai Lebak Bulus (Jakarta Selatan) dan Cempaka Mas, sementara Carrefour Duta Merlin cenderung biasa-biasa saja. Adapun Giant, gerai yang ada di deretan kawasan industri Jl. Raya Bogor (Cimanggis) selalu diwarnai antrean panjang di kasir.
Bagi para pemasok, hypermarket memang memberi daya tarik tersendiri karena beberapa keunggulan yang ditawarkan. Hal ini juga diakui Nani Samawathy, Manajer Merek PT Cahya Sakti Multiintrako (CSM) — pemasar furnitur merek Olympic. Selain melihat tren perubahan pola belanja dari tradisional ke modern market, CSM tertarik memasarkan produknya di hypermarket karena ada aspek promosinya. “Kami bisa melakukan displai produk sehingga harapannya bisa muncul impulse buying,” ujar Nani.
Alasan lain, sebagai pemimpin pasar, Olympic ingin menanamkan kebiasaan baru berbelanja furnitur. Jika biasanya orang belanja furnitur hanya di toko furnitur, CSM bermaksud membuat kebiasaan baru supaya orang belanja furnitur di hypermarket. Tak heranlah, produk Olympic (dan Olimpia) dipasarkan pula di berbagai hypermarket: Carrefour, Giant, Alfa, Makro dan Hypermart. Walau begitu, “Penjualan Olympic di hypermarket belum mencapai 20%,” ujar Nani sembari menyebut target penjualan CSM tahun ini sebesar Rp 1 triliun.
Tentu saja tak hanya Nani yang punya alasan kuat memasok hypermarket. Banyak pemasok melihat, menjual di hypermarket memungkinkan meraih omset dalam jumlah besar (miliaran) hanya melalui beberapa gerai yang mudah dikontrol. Hal ini dimungkinkan karena rata-rata gerai hypermarket Indonesia punya luas 5 ribu m2 — sesuai konsep aslinya, hypermarket punya format area penjualan 4-10 ribu m2.
Selain itu, bagi pemasok, bisa menjual produknya di hypermarket juga menjadi gengsi tersendiri karena berarti produknya diakui peritel modern. Mendisplai produk di hyppermarket juga bisa dilihat sebagai promosi below the line, serta sederet alasan lain. Namun dengan berbagai pertimbangan itu pula, di lain sisi, para pengelola hypermarket bisa melakukan banyak hal yang mereka rasa menguntungkan tapi tak enak buat pemasok.
Misalnya, karena merasa mampu menyerap produk dalam jumlah besar, mereka tak mau lagi membeli produk melalui perantara (distributor), tapi bila dimungkinkan akan deal langsung dengan menghubungi produsen. Para produsen tentu saja banyak yang tak bisa mengelak dengan tawaran seperti itu, sebab melihat potensi penjualan berjumlah besar. Di P&G Indonesia (PGI), sebut saja, seperti dikatakan Bambang Sumaryanto, Direktur PGI, juga menjual langsung beberapa produknya ke hypermarket selain melalui beberapa distributor, terutama produk Pampers Premium, Olay dan Shampoo kemasan botol.
Yang jelas, cara ini menjadi momok bagi para distributor independen karena fungsi mediasi yang merupakan sumber bisnisnya tiba-tiba dipotong hypermarket. Pada gilirannya pola bypass yang dilakukan para pengelola hypermarket berpengaruh pada keorganisasian produsen, karena kini ada tren baru di mana produsen membentuk divisi khusus yang menangani hypermarket dan biasanya ditangani seorang manajer tersendiri. Hampir semua perusahaan elektronik seperti Sanken, Samsung, Cosmos, Sony, melakukan hal yang sama, mengangkat manajer penjualan hypermarket.
Tak bisa dihindari, kuatnya posisi tawar-menawar pengelola hypermarket juga menyebabkan mereka sangat percaya diri terhadap para pemasok. Tak heranlah, mereka berani menekan para pemasok, terutama soal harga. Tujuannya jelas, pengelola hypermarket ingin mendapatkan harga seminimal mungkin agar bisa menelurkan harga jual yang rendah sehingga mudah berkompetisi dengan peritel lain.
Perlu dicatat, pola tekan-menekan pemasok oleh pengelola hypermarket ini bukan isapan jempol. Alasan klasiknya karena mereka bisa menjual dalam jumlah besar dan basis pelanggannya banyak. Seorang pengusaha muda, pemasok produk house brand Carrefour kategori makanan kering mengeluh saat ditemui SWA di sebuah seminar. “Terus terang, margin kami amat tipis karena harga kami ditekan. Tapi kami tetap suplai karena ordernya banyak sehingga tenaga kerja kami tetap ada kegiatan. Kami hitung sebagai promosi saja. Kalau dari keuntungan sebenarnya kecil banget,” keluhnya.
Dalam hal ini para pengelola hypermarket memang cukup cerdik. Harga yang ditawarkan antarpemasok sering diadu sehingga pemasok yang betul-betul ingin menjadi pemasok harus memberikan harga pada batas terbawah. Seperti dikatakan Djoko, kini timbul kekhawatiran di antara para produsen dengan makin kuatnya hypermarket. “Karena bisa beli dalam jumlah besar, mereka bisa menekan harga beli serendah mungkin sehingga bisa mengubah struktur kebijakan harga secara nasional,” ujar Djoko.
Posisi powerful kalangan hypermarket juga tampak dari keberaniannya menarik berbagai biaya (fee) ke para pemasok. Jika dulu hanya untuk keperluan produk-produk promo yang harus membayar, sekarang apa saja harus bayar. “Hypermarket meminta berbagai fee yang menjadi another income buat mereka. Ada yang disebut listing fee, opening fee, fix rebate, commond assortment fee dan fee untuk ulang tahun, dan entah apalagi,? seorang pengusaha pemasok alat-alat rumah tangga ke sejumlah hypermarket mengeluhkan.
Diakuinya, memang semua fee disebutkan dalam perjanjian awal dan ada proses negosiasi. “Namun terkadang negosiasinya bukan seperti negosiasi, tapi ada bahasa-bahasa yang kesannya pemaksaan tak langsung,” lanjut pengusaha peralatan rumah tangga itu. Sehingga, pada akhirnya pihak pemasok menyetujui dengan rasa terpaksa. ?Kalau tidak begitu, pemasok tidak bisa berjualan. Ini hampir semua pemasok merasakan,” kata pengusaha perabot yang ikut dalam seminar tersebut.
Susanto, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) menunjuk contoh sebuah hypermarket asing yang baru saja buka gerai di Surabaya. Ketika itu semua pemasok, termasuk pemasok lama diwajibkan bayar opening fee, per item produk Rp 3 juta. Kalau anggota AP3MI saja (300 orang) yang bayar opening fee, berarti hypermarket itu sudah mengantongi Rp 900 juta. Belum lagi dari pemasok lain nonanggota AP3MI. “Ini sangat memberatkan dan tidak adil,” ujar Susanto, yang melihat praktik seperti ini terutama dilakukan hypermarket asing karena pemain lokal lebih bijaksana.
Dengan alasan itu pula, sebuah perusahaan sosis terkemuka tak mau memasok ke hypermarket asing tersebut. Ketika itu manajemen perusahaan sosis ini sempat ingin menjadi pemasok, tapi dikenakan berbagai fee yang total berjumlah Rp 35 juta untuk tiga bulan. “Nanti kalau dalam tiga bulan produk kami tak laku sesuai target, produk kami di-delete, tak boleh dijual di outlet itu lagi. Sedangkan biaya Rp 35 juta tak bisa diminta lagi. Makanya kami lebih baik tak mau masuk,” tutur manajer penjualan perusahaan sosis itu.
Celakanya lagi, setelah membayar ini-itu para pemasok masih ?dikerjain? hypermaket dalam pemanfaatan SDM. Seharusnya urusan penataan produk di rak-rak dan space menjadi tanggung jawab hypermarket, apalagi pihak pemasok ditarik biaya macam-macam. Kenyataannya, pengelola hypermarket masih sering menyuruh merchandiser pemasok untuk menata dan merapikan barang dagangan di rak. Otomatis pihak pemasok rugi karena tenaga merchandiser yang seharusnya bisa memasok di banyak gerai sering kehabisan waktu. “Semula kami kira hanya kami yang ?dikerjain?. Setelah ngobrol dengan pemasok lain, ternyata diperlakukan sama,” ujar serorang GM perusahaan minuman terkemuka sembari menjelaskan hypermarket yang dimaksud ialah Carrefour.
Yang pasti, karena posisi bargaining-nya bagus, hypermarket sering pula mengulur-ulur pembayaran ke pemasok. Menarik menceritakan pengalaman manajemen Roti Buana yang sejak akhir tahun lalu tak lagi memasok ke hypermarket — padahal sebelumnya Roti Buana lama dipasarkan di berbagai hypermarket. “Term of payment-nya terlalu panjang,” alasan Ardi Buono, Manajer Operasional Nasional PT Candrabuana Suryasemesta –produsen Roti Buana.
Hal ini menjadi pertimbangan Roti Buana karena bahan baku bakery seperti tepung dan gula harus dibayar kontan kepada pemasok. Otomatis pembayaran dari hypermarket mestinya paling lama sebulan. Menurutnya, kalau masuk ke hypermarket pembayaran paling cepat 1,5 bulan sejak barang dipasok. Bahkan sering 2-3 bulan. Hal senada dikemukakan Nani dari Olympic, ?Term of payment hypermarket umumnya memang lelet. Biasanya di atas 45 hari.”
Nani menambahkan, pihaknya juga sering dirugikan bila ada perang harga antar-hypermarket. Dicontohkan Nani, bila hypermarket A menjual Olympic lebih murah dibanding harga di hypermarket B, maka hypermarket B akan menuduh pihak Olympic berlaku tidak fair. Dengan begitu biasanya hypermarket B langsung melakukan perubahan sehingga harga jual Olympic di hypermarket B sama dengan pesaingnya. “Restraksi inilah yang merugikan. Dan kami tidak bisa berbuat apa-apa,” ucap Nani kesal.
Kendati hypermarket banyak dikeluhkan, kenyataannya pemasok tetap tak mau meninggalkan begitu saja. “Dilema benci tapi rindu. Karena simbiosis mutualismenya juga ada, makin banyak gerainya, bisa menjangkau lebih banyak konsumen. Di lain pihak, biaya yang tersedot ke sana besar sekali,” papar Djoko. Bagaimanapun kini sebagai sebuah gerai, hypermarket merupakan marketplace yang dahsyat. Apalagi belakangan pada masa peak season sejumlah gerai hypermarket buka 24 jam. Di belakangnya rata-rata didukung tim pemasaran yang kuat.
Sekarang, hampir semua pengelola hypermarket telah mengeluarkan membership berupa kartu belanja. Makro, Club Store, Carrefour dan Alfa melakukannya. Malah, mereka juga percaya diri menarik iuran tahunan (annual fee) kepada anggota — Rp 25-60 ribu. Selain itu, kartu belanja yang mereka terbitkan bisa multifungsi. Misalnya Kartu Belanja Carrefour tidak sekadar sebagai kartu kredit yang bisa digunakan untuk berbelanja di 15 juta merchant di Indonesia dan luar negeri, melainkan bisa pula untuk menarik uang tunai di 200 ribu ATM, serta untuk kredit berjangka dan kredit cicilan.
Tentu saja, keberadaan kartu belanja ini di kalangan hypermarket akan lebih mudah ketika meluncurkan program khusus seperti program diskon atau trade-in karena segmen yang akan mereka bidik lebih jelas. Apalagi kenyataanya mereka berhasil meyakinkan para pelanggan, buktinya jumlah anggota tak bisa dibilang sedikit. Club Store sudah punya 60 ribu anggota. Sementara Makro dan Carrefour, basis anggotanya telah mencapai 600 ribu. Keberadaan kartu belanja ini jelas merupakan bagian dari cara mereka mengikat pelanggan agar makin loyal dan meningkatkan jumlah (nilai) pembelian. Jadi, merupakan cara cerdas meretensi pelanggan selain juga mengintensifikasi pemasaran.
Untuk memaksimalkan profit, pengelola hypermarket makin rajin pula mengembangkan house brand — produk yang diberi nama merek sesuai pesanan hypermarket, tapi bahan baku dan pabrikasinya dilakukan mitranya (tol manufacturing). Terutama untuk produk-produk yang permintaannya terbilang cepat seperti gula pasir, tisu, beras, dan sebagainya. Belakangan produk-produk peranti pertukangan pun mulai dibuat house brand.
Dalam hal ini masing-masing hypermarket memberi nama house brand berbeda-beda. Alfa tetap menamai produk-produk house brand-nya dengan nama Alfa. Sementara Carrefour punya BLUEsky dan Firstline, Hypermart memakai nama Value Plus, dan The Club Store menggunakan nama Club Pack. Makro paling banyak memiliki house brand, antara lain Aro, Savepack, Highstyle, Protect, Q-Biz, dan Tool Master. Dengan pola house brand, berarti hypermarket memotong biaya branding (promosi) yang sebelumnya dikeluarkan pemasok pemilik merek, dan persentase itu kemudian dikonversi menjadi tambahan profit buat hypermarket.
Bila disimak, mereka juga tak hanya jago dagang tapi juga pintar negosiasi dan punya trik-trik memobilisasi konsumen. Sebut saja dalam mempromosikan produk. Sering kali ada sejumlah produk yang dijual dengan harga menarik dipromosikan gencar di berbagai media, padahal jumlah barangnya terbatas.
Padahal sebenarnya produk tersebut hanya diposisikan sebagai gimmick agar pembeli datang ke gerai sehingga timbul impulse buying (pembelian yang tak direncana pembeli dari rumah). Selain itu dalam banyak item produk, hypermarket sengaja mengambil profit 0% agar dipersepsi sebagai gerai murah padahal di lain item ia juga meninggikan profitnya. Jadi ada pola subsidi silang.
Masih soal promosi, umumnya mereka menggandeng kalangan pemasok untuk promosi bersama dengan joint financing, sehingga mengurangi biaya yang harus dikeluarkan hypermarket. Kini, hampir semua ritel besar menjalankan strategi promosi yang mirip, mulai dari harga murah, undian, katalog dan iklan media. “Saya lihat persaingannya hingga saat ini tetap sehat, dan kesamaan strategi tersebut juga menunjukkan adanya kebijakan para pemasok yang berlaku hampir sama pada tiap ritel,” ujar Rullyanto Lukman, Presdir PT Alfa Retailindo — pengelola compact hypermarket Alfa.
Dari sisi besaran dana promosi, sejauh ini Carrefour memang paling agresif. Menurut data Nielsen Media Research, belanja iklan Carrefour mencapai Rp 36 miliar tahun 2003, dan sudah Rp 58 miliar hingga Oktober 2004. Sementara Alfa dan Giant belanja iklan tahunannya masih berkisar Rp 6-7 miliar.
Sementara itu Syamsul memprediksi, kemungkinan format ritel yang akan berkembang di masa mendatang cuma tiga jenis, yakni: hypermarket, specialty store dan minimarket. “Pemain yang tidak ikut pertempur dalam format ritel ini akan ketinggalan,” katanya menduga. Maka, ia mengingatkan bila Pasaraya dan Ramayana terlalu kaku dengan konsep lama akan ditinggal konsumen.
Dalam pandangan yang lebih ekstrem, Djoko melihat mungkin saja ke depan kondisi Indonesia mirip dengan Australia, 90% pasar ritel dikuasai hypermarket. Itu pun yang dominan hanya 3-4 pemain besar seperti Wal World, Cools, Pick & Pay (bahkan ini sudah diakuisisi Cools). Toko modern lain yang berkembang justru convenience store seperti 7 Eleven dan Circle K yang buka 24 jam.
Tentu Djoko — dan kita — tak berharap itu semua menjadi kenyataan karena harapannya antara berbagai ritel memiliki kontribusi yang seimbang, walaupun kenyataannya kini hypermarket sudah menjelma menjadi mesin uang baru yang dahsyat.
Gunakan ----{ CTRL + F }---- Untuk Mencari Artikel
----------------------------------------------------------------------------------
Postingan Baru :
- Cara membuat link berkedip ketika cursor melintas
- Cara Membuat Effect Snow Atau Tabur Salju Di Blog
- Cara Intalasi Windows Seven ( 7 ) Lengkap
- Code Rahasia Semua Type Handphone Lengkap
- Cara Daftar Dan Merubah Domain Blogspot Ke .CO.TV
- Cara Membuat Cursor Bertabur Bintang
- Cara Pasang Meta Tag Di Blogger SEO Friendly
- Cara Memasang Share Pack (Share Post To Social Boo...
- Cara memasang sharing is sexy di blogspot
- Cara Membuat Taskbar Ato Toolbar Melayang Di Blog
- Cara Membuat Shoutmix Tersembunyi
- Cara Membuat Link Warna - Warni Pelangi Di Blog
- Cara pasang video di blog
- Cara Membuat Link Berkedip Warna Warni
- Tempat Ganti Code Warna
- Cara Menu Tab View di Samping
- Cara Membuat Tulisan / text Berkedip
- Cara Membuat Menu Melayang
- Efek Marquee untuk Banner Berjalan
- Salam Pembuka Sesuai Dengan Settingan Waktu
- Mengganti Icon Blogger
- Cara membuat addres bar berjalan